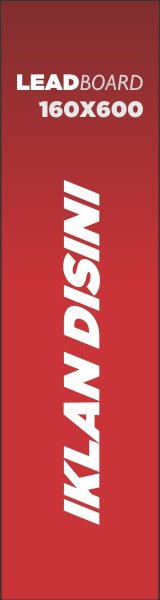Dalam sejarah seni dan budaya Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik yang menyertainya. Salah satu peristiwa penting yang menjadi titik persimpangan antara seni, budaya, dan politik adalah lahirnya Manifesto Kebudayaan (Manikebu) pada tahun 1963. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan perbedaan ideologis dalam dunia kebudayaan, tetapi juga menjadi cerminan dari pertarungan politik yang lebih luas di era tersebut.
Tetang Manikebu
Pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam situasi politik yang memanas. Presiden Soekarno semakin menegaskan garis politiknya yang anti-Barat dan berorientasi pada sosialisme. Dalam dunia kebudayaan, dominasi Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin kuat. Lekra mengusung prinsip bahwa seni harus berpihak kepada rakyat dan mendukung revolusi. Konsep ini dikenal dengan istilah “politik sebagai panglima,” yang berarti bahwa seni dan budaya harus tunduk pada kepentingan politik revolusioner.
Tidak semua seniman setuju dengan pendekatan tersebut. Kelompok seniman dan intelektual yang merasa bahwa seni harus memiliki kebebasan berekspresi dan tidak tunduk pada kepentingan politik tertentu kemudian merumuskan Manifesto Kebudayaan. Pada 17 Agustus 1963, manifesto ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh, seperti HB Jassin, Sutan Takdir Alisjahbana, Wiratmo Soekito, Trisno Sumardjo, dan lainnya. Mereka menegaskan bahwa seni harus berkembang secara bebas dan tidak menjadi alat propaganda politik.
Isi dan Tujuan Manifesto Kebudayaan
Manikebu menekankan bahwa kebudayaan harus berpijak pada prinsip universalitas dan kebebasan individu dalam berkarya. Para pendukungnya menolak dikte politik terhadap seni dan budaya. Beberapa poin utama dari manifesto ini antara lain:
- Kebudayaan harus berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal.
- Seni harus berkembang secara bebas tanpa intervensi politik.
- Kebudayaan adalah ekspresi dari keanekaragaman dan kreativitas individu, bukan alat politik atau ideologi tertentu.
Manifesto ini mendapatkan reaksi keras dari pihak-pihak yang mendukung konsep Lekra. Soekarno sendiri mengecam Manikebu dan menyebutnya sebagai gerakan kontra-revolusi. Para pendukung Manikebu mengalami tekanan politik yang besar, termasuk pemecatan dari pekerjaan, pembredelan karya, hingga pengasingan.
Manikebu dalam Konteks Perjuangan Seni dan Budaya
Manikebu bukan sekadar dokumen pernyataan sikap, tetapi juga simbol dari perjuangan kebebasan berkesenian di Indonesia. Di satu sisi, Lekra dengan pendekatan “politik sebagai panglima” berusaha menjadikan seni sebagai alat propaganda, sementara Manikebu menegaskan bahwa seni harus bebas dari belenggu politik. Benturan antara kedua kubu ini mencerminkan perdebatan klasik dalam dunia seni: apakah seni harus melayani ideologi tertentu, ataukah harus bebas berekspresi tanpa batasan?
Konflik antara Manikebu dan Lekra juga mengindikasikan bagaimana politik sering kali masuk ke dalam ruang kebudayaan dan mencoba mengendalikannya. Peristiwa ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain di dunia, di mana seni dan budaya sering menjadi alat politik bagi penguasa atau kelompok tertentu.
Dampak Politik terhadap Seniman Manikebu
Setelah G30S/PKI pada tahun 1965, situasi politik berubah drastis. PKI dilarang, dan pengaruh Lekra meredup. Namun, hal ini tidak serta-merta membuat para pendukung Manikebu mendapatkan posisi yang lebih baik. Rezim Orde Baru yang berkuasa setelahnya tetap mencurigai para seniman yang terlibat dalam Manikebu, karena mereka dianggap memiliki sikap yang tidak sejalan dengan pemerintah.
Banyak seniman Manikebu mengalami tekanan politik, meskipun tidak sekeras yang dialami oleh para seniman Lekra yang dituduh terlibat dengan PKI. Kebebasan berkesenian tetap menjadi isu yang sensitif, di mana rezim baru juga memiliki kepentingan dalam mengendalikan narasi seni dan budaya untuk mendukung legitimasi kekuasaan mereka.
Manikebu dan Relevansi di Era Sekarang
Meskipun terjadi lebih dari setengah abad yang lalu, perdebatan yang dipicu oleh Manikebu masih relevan hingga kini. Di era digital dan media sosial, kebebasan berekspresi kembali diuji dengan munculnya berbagai regulasi yang membatasi seni dan budaya dengan alasan moralitas, agama, atau kepentingan politik. Seniman dan budayawan masih harus berjuang untuk mempertahankan kebebasan berkarya tanpa intervensi dari pihak yang berkepentingan.
Selain itu, perkembangan teknologi telah menciptakan tantangan baru dalam dunia seni dan budaya. Sensor digital, algoritma media sosial, serta tekanan dari kelompok-kelompok tertentu membuat seniman harus lebih kreatif dalam menyampaikan gagasannya. Prinsip yang diusung oleh Manikebu—bahwa seni harus bebas dari belenggu politik—masih menjadi isu penting di berbagai belahan dunia.
Kesimpulan
Manikebu adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah seni dan budaya Indonesia yang menunjukkan bagaimana seni, budaya, dan politik saling berinteraksi dan berbenturan. Perjuangan para seniman Manikebu untuk mempertahankan kebebasan berkarya menghadapi tantangan besar, tetapi warisan pemikiran mereka masih hidup hingga saat ini. Di tengah arus politik yang terus berubah, prinsip kebebasan berkesenian tetap menjadi hal yang harus diperjuangkan oleh para seniman dan budayawan di Indonesia dan dunia.
Dalam perjalanan sejarah, seni dan budaya selalu memiliki relasi yang kompleks dengan politik. Tantangan terbesar bagi seniman adalah bagaimana tetap menjaga kebebasan berekspresi tanpa kehilangan relevansi di tengah dinamika sosial dan politik yang ada. Sejarah Manikebu mengajarkan bahwa seni yang bebas adalah seni yang mampu bertahan dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan peradaban.